Belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka, pers kita dalam kurun waktu yang cukup lama tidak lagi mengalami tekanan dari pemerintah. Barulah sekarang ini, sudah hampir 11 tahun pers kita mendapat peluang untuk sepenuhnya memanfaatkan kebebasan pers. Pemberedelan pers, seperti juga sensor dan penghentian siaran oleh siapa pun, dilarang oleh Undang-Undang (UU) Pers yang berlaku sekarang. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang disetujui DPR 13 September 1999 dan disahkan oleh Presiden Habibie 10 hari kemudian, dengan tegas menyatakan (Pasal 4 Ayat 2): “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran.” Sebelumnya, UU Pokok Pers Tahun 1966 dan Tahun 1982 juga menegaskan ketentuan yang sama, dan untuk penerbitan, pers “tidak memerlukan Surat Izin Terbit.” Akan tetapi, ketentuan tentang SIT tersebut dalam undang-undang tahun 1966 dikaburkan oleh Pasal 20 Ayat (1)-a yang berisi, “Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR (GR).” Ayat itu dihapus dalam undang-undang tahun 1982. Akan tetapi, sebaliknya, undang-undang ini menetapkan pada Pasal 13 Ayat (5) bahwa “Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang dikeluarkan oleh Pemerintah.” Ketentuan SIT dan SIUPP ini terus berlaku sampai akhir masa Orde Baru dan lahirnya UU Pers tahun 1999. Undang-undang pers yang membatasi kebebasan pers pada masa Indonesia merdeka baru dilahirkan pada 12 Desember 1966. Namun, tekanan terhadap pers sudah dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Surat kabar Revolusioner yang terbit di Yogyakarta, dilarang beredar ketika memuat tulisan yang menyebut Presiden Soekarno “bombastis”. Koran Soeara Moeda di Solo diberedel dengan tuduhan pro swapraja, ketika di kota itu orang sedang gandrung anti-swapraja. Harian Soeara Rakyat edisi Kediri diberedel beberapa hari oleh gubernur militer Jawa Timur karena memuat berita penembakan mati Muso, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memimpin pemberontakan di Madiun. Pemerintah RI di Yogyakarta pada September 1948 memberedel tiga surat kabar lokal yang berhaluan politik kiri: Revolusioner, Patriot, dan Soeara Iboekota.
Lisensi Orde Lama dan Orde Baru Kebebasan pers tetap tidak terjamin setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949. Selama beberapa tahun berikutnya terjadi penutupan kantor berita dan sejumlah surat kabar. Juga penahanan terhadap sejumlah wartawan kita dan pengusiran terhadap beberapa wartawan asing. Pada 1957, tercatat 20 kasus pemberedelan sementara di Jakarta dan 11 kasus pers di luar Ibu Kota. Mochtar Lubis, pemimpin redaksi harian Indonesia Raya, dikenai tahanan rumah dan dipenjarakan selama sembilan tahun hampir terus-menerus karena disangka “terlibat komplotan Zulkifli Lubis.” Pada 1958, 12 surat kabar di Jakarta dilarang terbit sementara. Sementara itu di daerah, tercatat 21 kasus penindakan terhadap pers. Selama tahun 1959, dilakukan pemberedelan terhadap 25 surat kabar di Jakarta dan enam surat kabar daerah. Selain pemberedelan, juga ada keharusan pemilikan izin terbit bagi media pers cetak. Pada 1 Oktober 1958, semua surat kabar dan majalah harus didaftarkan kepada Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya) untuk memperoleh Surat Izin Terbit (SIT). SIT akhirnya diberlakukan di seluruh Indonesia mulai 12 Oktober 1960 berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 10 Tahun 1960. Inilah awal pemberlakuan lisensi bagi media pers cetak di Indonesia pada masa merdeka. Sebelum ini, hanya pernah terjadi pada masa pendudukan militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. Tidak ada lisensi seperti ini pada masa penjajahan Belanda. Pada Februari 1965, Presiden Soekarno memerintahkan penutupan koran-koran pendukung Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang dituduh anti-Soekarnoisme. Menjelang akhir tahun 1965, ketika berlangsung masa transisi ke Orde Baru, 46 surat kabar—dari 163 surat kabar yang ada di seluruh Indonesia—diberedel tanpa batas waktu. Kebanyakan yang diberedel adalah terbitan Partai Komunis Indonesia, atau dianggap bersimpati kepada PKI, atau “tidak menaati Undang-Undang Pers.” Larangan terbit terhadap media pers hampir terus-menerus berlangsung selama masa Orde Baru dan barulah berakhir dengan penutupan dua majalah berita, Tempo dan Editor, serta tabloid politik Detik pada 1994.
Tekanan Hukum, Pengusaha, dan Publik
Walaupun tekanan dari pemerintah terhadap media pers diharapkan benar-benar berakhir pada masa Reformasi, kebebasan pers kita belum sepenuhnya terlindungi dan terjamin. Masih ada tekanan-tekanan lain yang menggelisahkan para pengelola media pers kita. Tekanan ini dapat berasal dari apa yang disebut sebagai kriminalisasi pers, yaitu penggunaan hukum pidana yang represif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat memenjarakan wartawan karena karya jurnalistiknya sampai maksimal tujuh tahun. Tekanan juga dapat berasal dari para pengusaha yang lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan media pers. Jalur hukum pidana memungkinkan wartawan mendapat sanksi penjara, sedangkan jalur hukum perdata dapat menyebabkan perusahaan pers terkena sanksi denda yang tinggi. Jika hukuman denda sedemikian tinggi, itu akan membangkrutkan perusahaan pers, maka akibat yang dialami media pers tidak ubahnya seperti pemberedelan melalui jalur hukum. Tekanan lain yang agak sering terjadi, terutama pada tahun-tahun awal Reformasi, berasal dari publik yang melakukan aksi kekerasan. Harian Jawa Pos di Surabaya pernah tidak terbit satu edisi karena para wartawannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya ketika didemonstrasi sampai hampir tengah malam sebagai protes terhadap berita yang tidak akurat. Harian Radar Sulteng di Palu menghentikan penerbitannya selama tiga hari karena tekanan para demonstran yang memprotes satu tulisan. Tabloid Bijak di Padang tidak pernah terbit lagi sejak peralatan kantornya dirusak oleh para demonstran. Radio Rasitania FM di Solo menghentikan siaran selama satu minggu atas tuntutan para demonstran yang menentang satu talkshow tentang agama. Kita berharap bahwa tekanan-tekanan ini, terlebih lagi tindakan kekerasan oleh massa, lambat laun akan berakhir sejalan dengan pemahaman kita terhadap makna pers yang kritis dan independen di sebuah negara demokrasi. Memang, ketidakpahaman di kalangan masyarakat tentang kedudukan pers sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi publik hingga kini masih berkembang. Hak jawab atau klarifikasi dari subjek berita yang ingin mengemukakan versinya adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi.
Penulis adalah pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), dan Ketua Dewan Pengurus Voice of Human Rights (VHR) News Centre di Jakarta.




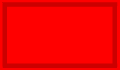












0 komentar
Posting Komentar